
Thalasemia merupakan penyakit menurun, yang ditandai gangguan produksi eritrosit & hemoglobin.
DEFINISI
Thalasemia merupakan penyakit menurun yang ditandai dengan gangguan dan ketidakmampuan memproduksi eritrosit dan hemoglobin.
Kelainan darah yang ditandai dengan kondisi sel darah merah yang mudah rusak, yaitu 3-4 kali lebih cepat dibanding sel darah normal. Oleh karena itu umurnya pun relatif lebih pendek dibanding sel darah normal. Jika sel darah normal memiliki umur 120 hari, maka sel darah merah penderita thalasemia hanya bertahan 23 hari.
Sel darah merah yang rusak diuraikan menjadi zat besi didalam limpa. Karena kerusakan darah terjadi dengan cepat dan massif, maka kandungan zat besi dalam tubuh menumpuk dan bisa mengganggu fungsi organ lain sehingga berujung pada kematian.
PENYEBAB PENYAKIT THALASEMIA
Thalasemia bukanlah penyakit menular, namun disebabkan oleh faktor keturunan (genetic). Pasien thalasemia sendiri banyak ditemukan didaerah miskin. Begitu juga dengan daerah endemis malaria. Daerah endemis malaria merupakan daerah yang sangat rentan terjadi kasus thalasemia. Parasit malaria diduga ikut membantu kerusakan sel darah merah.
Sayangnya hingga saat ini thalasemia belum bisa diobati untuk penyembuhan. Bahkan, pada banyak kasus penderita thalasemia mayor tidak berhasil mencapai usia tua dan meninggal pada usia 19-30 tahun.
Namun kasus kematian bukan karena penyakit thalasemianya, tapi karena komplikasi kerusakan organ akibat penumpukan zat besi yang berlebihan di dalam organ tubuh. Namun agar penderita tetap produktif, dibutuhkan transfusi darah secara teratur setiap bulan selama hidupnya. Pengobatan yang efektif bisa memperpanjang usia harapan hidup hingga 40-50 tahun.
JENIS THALASEMIA Skema turunan penyakit thalasemia Thalasemia dibedakan berdasarkan gejala klinis dan tingkat keparahannya yakni thalasemia mayor dan thalasemia minor. Thalasemia mayor yakni mayor dimana kedua orang tuanya merupakan pembawa sifat, serta thalasemia minor dimana gejalanya jauh lebih ringan dan hanya sebagai pembawa sifat saja.
Pada thalasemia mayor gejala dapat timbul sejak awal masa anak-anak, namun kemungkinan untuk bertahan hidup terbatas. Beberapa kasus yang ditemukan selama ini juga membuat timbulnya penggolongan yang lebih baru, yakni thalasemia intermedia, yakni dimana kondisinya berada diantara kedua bentuk thalasemia mayor dan minor.
Penderita thalasemia ini dibedakan berdasarkan produksi jenis globin yang terganggu. Jika mengalami produksi globin jenis alfa yang terganggu, maka penderitanya mengalami thalasemia alfa, sedangkan jika mengalami produksi globin jenis beta yang terganggu, maka penderitanya mengalami thalasemia beta.
Disamping itu thalasemia juga dibedakan berdasarkan jenis mayor dan minor, diantaranya adalah :
GEJALA THALASEMIA
Gejala thalasemia terjadi bervariasi tergantung dari jenis thalasemia yang diderita, selain itu dilihat pula dari segi derajat kerusakan gen yang terjadi. Awalnya penyakit thalasemia menunjukkan gejala seperti anemia yakni :
Tulang muka merupakan tulang pipih. Tulang pipih berfungsi memproduksi sel darah. Akibat thalasemia, tulang pipih akan berusaha memproduksi sel darah merah sebanyak-banyaknya hingga terjadi pembesaran tulang pipih. Pada muka, hal ini dapat dilihat dengan jelas karena adanya penonjolan dahi, menjauhnya jarak antara kedua mata, dan menonjolnya tulang pipi (wajah mongoloid)
 Limpa berfungsi membersihkan sel darah yang rusak. Pembesaran limpa pada penderita thalasemia terjadi karena sel darah merah yang rusak sangat berlebihan sehingga kerja limpa sangat berat. Selain itu, tugas limpa juga lebih di perberat untuk memproduksi sel darah merah lebih banyak. PENCEGAHAN THALASEMIA.
Memang, hingga saat ini Thalasemia tidak bisa disembuhkan. Untuk itu diperlukan pencegahan penyebarannya. Penyebaran penyakit ini hanya bisa dilakukan dengan mencegah mereka yang memiliki gen carier Thalasemia sebaiknya tidak menikah dengan sesama pembawa sifat penyakit (carier). Perkawinan dua pembawa sifat-sifat penyakit bisa memungkinkan terlahir anak dengan Thalasemia Mayor (Thalasemia berat).
Yang mengkhawatirkan penyakit ini sebenarnya banyak dialami penduduk negara bekembang termasuk Indonesia. Bahkan hingga saat ini jumlah penderitanya pun terus bertambah. Hingga saat ini thalasemia belum bisa disembuhkan. Secara epidemologi jarang sekali penderita thalasemia yang berhasil mencapai usia lanjut. Meskipun demikian pasien thalasemia tetap harus diobati dan ditanggulangi penyebarannya
Selanjutnya upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak pemberian konseling dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memeriksakan diri apakah memiliki gen pembawa thalasemia atau tidak  Skema gen penurunan penyakit thalasemia
Penjelasan gambar :
PENGOBATAN THALASEMIA
Pengobatan yang paling optimal adalah transfusi darah seumur hidup. Kelahiran penderita thalasemia dapat dicegah dengan dua cara.
Pertama, mencegah perkawinan antara dua orang pembawa sifat thalasemia. Kedua, memeriksa janin yang dikandung oleh pasangan pembawa sifat dan menghentikan kehamilan janin bila dinyatakan sebagai penderita thalasemia
sumber :
http://thalasemia.org/
http://www.reliance-insurance.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Athalasemia&catid=8%3Abottom-newsflash&Itemid=10&lang=in
|
This is featured post 1 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.

This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.

This is featured post 3 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.

Senin, 17 Desember 2012
Thalasemia
Fungsi Sistem Peredaran Darah pada Manusia
Secara umum, sistem peredaran darah berfungsi mengangkut makanan dan zat sisa hasil metabolisme. Selain itu, sistem peredaran darah juga berfungsi sebagai berikut.
- Mengangkut zat buangan dan substansi beracun menuju hati untuk didetoksifikasi (dinetralkan) atau ke ginjal untuk dibuang.
- Mendistribusikan hormon dari kelenjar dan organ yang memproduksinya ke sel-sel tubuh yang membutuhkannya.
- Mengatur suhu tubuh melalui aliran darah.
- Mencegah hilangnya darah melalui mekanisme pembekuan darah.
- Melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasikan antibodi dan sel darah putih.
Pada prinsipnya, sistem peredaran darah memiliki empat komponen utama sebagai berikut.
- Darah, berfungsi sebagai medium pengangkut untuk nutrisi, udara, dan zat buangan.
- Jantung, berfungsi memompa darah sehingga dapat beredar ke seluruh tubuh.
- Pembuluh darah, merupakan saluran tempat darah beredar ke seluruh tubuh.
- Sistem lain yang dapat menambah atau mengurangi kandungan dalam darah. Misalnya, usus halus dalam sistem pencernaan tempat darah mendapatkan nutrisi yang akan dibawa ke seluruh tubuh, atau ginjal tempat darah mengurangi konsentrasi urea yang dikandungnya.
1. Komposisi Darah. Manusia rata-rata mempunyai lima sampai enam liter darah, atau sekitar 8% dari total berat badannya. Apabila darah diendapkan dengan proses sentrifugasi, darah terbagi menjadi dua bagian, yaitu plasma darah dan sel sel darah (Starr and Taggart, 1995: 656). Perhatikan Gb 5.1.
Gb. 5.1 Ketika darah disentrifugasi, akan terbentuk lapisan-lapisan darah, yaitu plasma darah dan sel-sel darah
Komponen
|
Jumlah
|
| Plasma darah (50%–60% volume darah) | |
| 1. Air | 91%–92% plasma darah |
| 2. Protein | 7%–8% plasma darah |
| 3. Ion, gula, lemak, asam amino, hormon, vitamin, | 1%–2% plasma darah |
| dan gas terlarut | 4-5 juta sel/mL darah |
| Sel darah (40%–50% volume darah) | |
| 1. Sel darah merah | 3.000–6.750 sel/mL darah |
| 2. Sel darah putih | 250.000–3.000 sel/mL darah |
| 3. Trombosit |
a. Plasma Darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang paling banyak, yaitu sekitar 55%-60% bagian dari darah. Plasma darah terdiri atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalamnya yang harus diangkut ke seluruh tubuh. Zat-zat terlarut dalam plasma darah tersebut terdiri atas protein, hormon, nutrisi (glukosa, vitamin, asam amino, lemak), gas (oksigen dan karbon dioksida), garam-garam (sodium, kalsium, potasium, magnesium), serta zat buangan seperti urea. Protein dalam plasma darah merupakan zat terlarut yang paling banyak. Terdapat tiga bagian utama protein plasma darah, yaitu:
1) albumin, berperan dalam mengatur tekanan osmotik darah (mengontrol aliran air yang masuk ke dalam membran plasma);
2) globulin, mengangkut nutrisi makanan dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh;
3) fibrinogen, berperan dalam proses pembekuan darah.
1) albumin, berperan dalam mengatur tekanan osmotik darah (mengontrol aliran air yang masuk ke dalam membran plasma);
2) globulin, mengangkut nutrisi makanan dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh;
3) fibrinogen, berperan dalam proses pembekuan darah.
b. Sel-Sel Darah. Hampir 45% dari volume darah manusia merupakan sel-sel darah. Darah mengandung beberapa tipe sel darah yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Terdapat tiga macam sel darah, yaitu sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), dan keping darah (trombosit).
1) Sel darah merah. Eritosit (erythro = merah, cyto = sel) tidak memiliki inti sel dan berbentuk bikonkaf sehingga memiliki luas permukaan yang besar (Gambar 5.2). Pria rata-rata mempunyai eritrosit ± 5 juta per mm3 darahnya, sedangkan wanita mempunyai eritrosit ± 4,5 juta per mm3 darahnya. Mengapa bisa demikian?
Gb. 5.2 Sel-sel darah merah berwarna merah dan berbentuk bikonkaf.
Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin, yaitu sebuah molekul kompleks dari protein dan molekul besi (Fe). Setiap molekul hemoglobin dapat berikatan dengan empat molekul oksigen. Oksigen diperoleh ketika sel darah melewati kapiler-kapiler alveolus di paruparu. Hemoglobin kurang reaktif terhadap molekul karbon dioksida. Oleh karena itu, karbon dioksida yang diperoleh dari sel lebih banyak larut dalam plasma darah.
Gb. 5.3 Setiap hemoglobin dapat mengikat empat molekul oksigen.
Hemoglobin yang berikatan dengan oksigen akan berwarna merah cerah. Adapun hemoglobin yang tidak berikatan dengan oksigen, berwarna merah gelap atau kebiru-biruan. Sel darah merah dibentuk dalam sumsum tulang. Sel darah merah tidak mempunyai inti sel sehingga sel darah merah tidak dapat hidup lama. Sel darah yang mati atau rusak dikeluarkan dari sistem peredaran darah. Kemudian, masuk ke hati atau limfa untuk dipecah. Zat besi yang dikandung sel darah tersebut kemudian diangkut darah menuju sumsum tulang untuk dirakit kembali menjadi molekul hemoglobin yang baru hingga akhirnya terbentuk sel darah yang baru.
2) Sel Darah Putih. Sel darah putih tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna merah, serta ukuran dan jumlah sel darah putih berbeda dengan sel darah merah. Perbandingan jumlah sel darah putih dan sel darah merah mencapai 1:500 hingga 1:1000. Artinya, terdapat 500 hingga 1000 sel darah merah untuk setiap satu sel darah putih. Ukuran sel darah putih lebih besar daripada sel darah merah. Sel darah putih memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sel darah putih berdasarkan karakteristik sitoplasmanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit.Granulosit merupakan kelompok sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula. Granulosit terdiri atasneutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil adalah sel darah putih yang granulanya menyerap zat warna yang bersifat netral. Sementara itu, eosinofil granulanya menyerap zat warna yang bersifat asam, sedangkan basofil granulanya menyerap zat warna yang bersifat basa. Sementara itu, agranulosit merupakan kelompok sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula, terdiri atas limfosit dan monosit. Limfosit dinamai demikian karena sel ini terdapat juga pada cairan limfa. Adapun monosit merupakan sel darah putih yang berukuran besar.
Gambar 5.4 Terdapat lima tipe leukosit, yaitu (a) neutrofil, (b) eosinofil, (c) basofil, (d) limfosit, dan (e) monosit.
Sel darah putih dibentuk di limfa dan sumsum tulang. Secara umum, sel darah putih berperan dalam pertahanan tubuh. Sel darah putih akan mematikan organisme atau zat asing berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, terutama yang masuk melalui jaringan darah. Eosinofil dan monosit dapat bersifat fagositik terhadap sel asing, seperti sel bakteri dan sel kanker. Dalam melaksanakan fungsinya, monosit dapat membesar menjadi makrofag.
3) Keping Darah. Keping-keping darah (trombosit) merupakan fragmen-fragmen besar sel yang disebutmegakariosit. Jadi, keping-keping darah bukan merupakan satu sel yang utuh. Seperti sel darah merah, keping-keping darah tidak mempunyai inti sel dan masa hidupnya pun pendek, yaitu sekitar 10–12 hari. Keping-keping darah berperan dalam proses penghentian pendarahan. Pembekuan dimulai ketika keping-keping darah dan faktor-faktor lain dalam plasma darah kontak dengan permukaan yang tidak biasa, seperti pembuluh darah yang rusak atau terluka. Ketika ada permukaan yang terbuka pada pembuluh darah yang terluka, keping-keping darah segera menempel dan menutupi permukaan yang terbuka tersebut. Keping-keping darah yang menempel, faktor lain, dan jaringan yang terluka memicu pengaktifan trombin, sebuah enzim, dari protrombin dalam plasma darah. Trombin yang terbentuk akan mengkatalis perubahanfibrinogen menjadi benang-benang fibrin.
Molekul fibrin menempel satu sama lain, membentuk jaringan berserat. Jaringan protein fibrin ini, menghentikan aliran darah dan membuat darah menjadi padat, seperti gelatin ketika sudah dingin. Jaringan ini membuat sel darah merah terperangkap dan menambah kepadatan dari darah yang beku. Untuk memahami proses pembekuan darah, perhatikan Gb 5.5.
Gb. 5.5 Luka dapat memicu pembekuan darah.
Keping-keping darah menempel di bagian yang berserat dan mengeluarkan benang-benang yang lengket dan membuatnya merekat satu dengan yang lain. Dalam waktu setengah jam, keping-keping darah mengerut, menarik lubang untuk merapat, dan memaksa cairan yang ada untuk keluar. Aksi tersebut menghasilkan pembekuan yang padat dan kuat sehingga membuat luka merapat.
2. Golongan Darah. Golongan darah pada manusia ditentukan oleh protein spesifik yang terdapat di membran sel darah merah. Pada awal abad ke-19, Karl Landsteiner, seorang ilmuwan Australia bersama dengan Denath, mengelompokkan darah menjadi empat tipe, yaitu A, B, AB, dan O. Hal tersebut bergantung pada ada-tidaknya protein spesifik dalam membran plasma pada sel darah merah yang disebut aglutinogen(antigen). Antigen merupakan molekul yang menyebabkan pembentukan antibodi (aglutinasi). Jika seseorang memiliki aglutinogen A di sel darah merahnya, dalam plasma darah akan terbentuk aglutinin Batau biasa dikenal dengan anti-B. Orang tersebut memiliki golongan darah A. Sebaliknya, jika terdapataglutinogen B, orang tersebut bergolongan darah B dan memiliki aglutinin A atau anti–A. Sementara itu, orang yang memiliki aglutinogen A dan B, ia tidak memiliki anti–A maupun anti–B, dan golongan darahnya adalah AB. Bagaimana dengan orang yang bergolongan darah O? Untuk lebih jelasnya, perhatikan Tabel 5.1.
Tabel 5.1 Golongan Darah dan Kandungan Aglutinogen – Aglutinin
No.
|
Golongan Darah
|
Aglutinogen pada Eritrosit
|
Aglutinin pada Plasma Darah
|
| 1 | O | - | anti-A dan anti-B |
| 2 | A | A | anti-B |
| 3 | B | B | anti-B |
| 4 | AB | A dan B |
Jika golongan darah yang berbeda dicampurkan, darah-darah tersebut biasanya menggumpal. Proses menggumpalnya darah ini disebut aglutinasi. Jika darah dari golongan yang sama dicampurkan, penggumpalan tidak terjadi. Pada 1940, Dr. Landsteiner menemukan bahwa golongan darah A juga dapat diberikan kepada kera Macaca rhesus. Akan tetapi, 15% dari jumlah sampel mengalami penggumpalan. Dr. Landsteiner menemukan bahwa sampel yang mengalami penggumpalan tersebut tidak memiliki faktor Rh dalam darahnya. Darah yang demikian disebut dengan rh-. Hanya darah yang mengandung faktor Rh (rh+) yang dapat menjadi donor bagi kera Macaca rhesus. Sistem rhesus ini sangat penting diperhatikan oleh ibu hamil. Jika darah ibu tersebut rh–, sedangkan anaknya rh+, dikhawatirkan ada antigen rh+ anak yang masuk ke dalam darah ibu. Akibatnya, akan dibentuk aglutinin rh di tubuh ibu. Kondisi ini akan membahayakan anak yang dikandungnya. Pada kehamilan pertama, kemungkinan besar anak yang dilahirkan akan selamat karena belum banyak terbentuk anti-rh di tubuh ibu. Pada kehamilan kedua dan seterusnya, risiko terjadi penggumpalan pada darah bayi semakin besar karena anti-rh yang terbentuk di tubuh si ibu semakin banyak ini dinamakan eritroblastosis fetalis (Gb. 5.6).
Gambar 5.6 (a) kehamilan pertama fetus dapat selamat. (b) kehamilan kedua, fetus akan mengalami eritroblastosis fetalis.
Dari pengetahuan golongan darah ABO dan Rh inilah pemberian dan penerimaan darah antarmanusia dapat dilaksanakan. Pemberian dan penerimaan darah ini disebut transfusi darah.
Tabel 5.2 Kemungkinan Transfusi Darah
| Donor | Resipien | |||
| A | B | AB | O | |
| A | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| B | - | ✓ | ✓ | |
| AB | - | - | ✓ | - |
| O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ket: ✓ = dimungkinkan (darah tidak menggumpal)
- = tidak dimungkinkan (darah menggumpal)
- = tidak dimungkinkan (darah menggumpal)
sumber : http://budisma.web.id/materi/sma/biologi-kelas-xi/fungsi-sistem-peredaran-darah-pada-manusia/
Proses Fertilisasi dan Kehamilan pada Manusia
Fertilisasi terjadi jika sel telur bertemu dengan sel sperma. Pada manusia, proses Fertilisasi didahului dengan proses senggama. Penis harus berada dalam keadaan tegak (ereksi), agar dapat mengantarkan sperma ke dalam vagina. Penis ereksi disebabkan oleh melebarnya arteri dan menutupnya pembuluh vena di penis. Dengan demikian ada banyak aliran darah yang masuk dan sedikit darah yang dikeluarkan (ditahan dalam pembuluh darah penis). Pembuluh darah juga akan memenuhi jaringan di dalam penis sehingga penis mengalami pemanjangan dan berubah menjadi lebih keras. Jika penis sudah ereksi, proses senggama dapat dilakukan. Pada saat penis memasuki vagina, reseptor di penis akan menerima rangsangan sentuhan yang menyebabkan dikeluarkannya semen yang berisi jutaan sel sperma. Proses keluarnya semen tersebut dinamakan ejakulasi.
Pada lelaki normal, dalam satu kali ejakulasi akan dikeluarkan 300 juta – 400 juta sel sperma. Pergerakan sel sperma di dalam vagina dibantu oleh semen dan cairan pelicin yang dihasilkan oleh cervix. Cairan pelicin tersebut akan disekresikan oleh kelenjar di cervix jika seorang wanita telah siap melakukan senggama atau mendapat rangsangan seksual. Sel sperma akan berenang menuju oviduk atau tuba Fallopi tempat sel telur berada setelah masa ovulasi. Oviduk atau tuba Fallopi merupakan tempat fertilisasi pada manusia. Pergerakan sel sperma didukung oleh ekor sperma yang banyak mengandung mitokondria penghasil ATP. Sel telur yang diovulasikan umumnya masih berada pada tahap meiosis II dan belum sepenuhnya menjadi oosit. Dengan adanya peleburan sel sperma, proses meiosis II dapat dipercepat. Sel telur yang telah siap dibuahi akan membentuk zona pelindung yang dinamakan corona radiata di bagian luar serta sebuah cairan bening di dalamnya yang disebut zona pelusida.
Sel sperma yang telah mencapai sel telur akan berlomba untuk dapat memasuki zona pelusida (Gambar 10.10). Zona pelusida mempunyai reseptor yang bersifat “spesies spesifik”, yaitu hanya dapat dilalui oleh sel sperma dari satu species. Akrosom sperma mempunyai enzim litik yang mampu menembus corona radiata dan zona pelusida.
Pada saat sel sperma menembus corona radiata, akrosom sperma akan meluluh. Sel telur kemudian akan segera menyelesaikan tahap meiosis II menghasilkan inti fungsional yang haploid. Bagian inti sel sperma ini kemudian bersatu dengan membran sel telur untuk melakukan fusi materi genetik. Gerakan ini mirip dengan mekanisme endositosis pada sel. Setelah terjadi peleburan atau fertilisasi ini, corona radiata akan menebal sehingga tidak ada lagi sel sperma lain yang dapat masuk. Pada saat ini sel tersebut sudah dibuahi dan berubah menjadi zigot. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula. Zigot ini kemudian melakukan pembelahan sel selama perjalanannya di oviduk menuju rahim. Pergerakan zigot menuju rahim (uterus) tersebut memakan waktu 4 hari. Dalam waktu 1 minggu, zigot telah berbentuk seperti bola yang dinamakanblastula. Blastula memiliki rongga yang disebut blastosol. Masa sel di bagian dalam blastosol, akan menjadi bakal embrio.
Bagian lengket dari blastosol tersebut kemudian akan menempel di endometrium. Proses tersebut dinamakanimplantasi. Blastula selanjutnya berkembang membentuk tiga lapisan, yaitu lapisan luar (ektoderm), lapisan tengah (mesoderm), dan lapisan dalam (endoderm). Tahap ini disebut gastrulasi yang terjadi sekitar minggu ketiga.
Selanjutnya, ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung. Mesoderm membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. Sementara itu, endoderm akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis. Organogenesis dimulai dari minggu keempat hingga minggu kedelapan dan penyempurnaan pada minggu kesembilan (Gambar 10.12).
 Gambar 10.12 Perkembangan zigot hingga menjadi janin yang dimulai dari umur (a) 2 minggu, (b) 5 minggu, (c) 9 minggu, dan (d) 20 minggu.
Gambar 10.12 Perkembangan zigot hingga menjadi janin yang dimulai dari umur (a) 2 minggu, (b) 5 minggu, (c) 9 minggu, dan (d) 20 minggu.
Embrio akan melepaskan hormon corionic gonadotropin (hormon yang mirip dengan LH) yang akan dibawa ke ovarium untuk mencegah luluhnya corpus luteum. Dengan demikian, estrogen dan progesteron tetap dihasilkan sehingga dapat mempertahankan persiapan kehamilan di rahim dengan mempertahankan ketebalan endometrium. Dari manakah embrio memperoleh suplai makanan?
Kehamilan terjadi mulai dari fertilisasi hingga kelahiran. Pada manusia, rata-rata kehamilan terjadi selama 266 hari (38 minggu) dari fertilisasi atau 40 minggu dari siklus menstruasi terakhir hari pertama. Kelahiran bayi terjadi melalui serangkaian kontraksi uterus yang beraturan. Beberapa hormon, seperti estrogen, oksitosin, dan prostaglandin berperan dalam proses ini. Secara umum, proses kelahiran terjadi melalui tahap pembukaan cervix, tahap pengeluaran bayi, dan tahap pelepasan plasenta (Gambar 10.13).
Pemberian ASI (Air Susu Ibu)
Semenjak bayi dilahirkan, ia tidak lagi diberi nutrisi melalui plasenta. Namun, sang ibu masih dapat memberi makan bayi dengan memproduksi dan menyekresikan susu dari payudaranya. Di dalam payudara, terkandungkelenjar mamae. Kelenjar mamae (kelenjar susu) berada di lapisan kulit dan menyekresikan campuranlemak, protein, dan karbohidrat yang dikenal dengan air susu. Berikut tabel kandungan nutrien dalam ASI.
Gambar 10.14 Persentase kandungan ASI
Tabel 10.1 Beberapa Zat yang Dikandung Kolostrum dan ASI
| Kandungan | Manfaat |
| Kolostrum• Immunoglobulin A• Protein, vitamin A, karbohidrat, dan lemak | Zat kekebalan untuk melindungi bayi dan berbagai penyakitterutama diare.Sesuai kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran. |
| ASI• Taurin• Decosahexanoic Acid (DHA)dan Arachidonic Acid (AA)• Immunoglobulin A (Ig.A)• Laktoferin• Lisozim • Sel darah putih • Faktor bifidus | Asam amino, berfungsi sebagai neurotransmiter dan proses pematangan otak Asam lemak tak jenuh rantai panjang untuk pembentukan sel-sel otak yang optimal. Dapat dibentuk oleh tubuh dari substansi pembentuknyaprecursor), yaitu masing-masing dari omega 3 (asam linolenat) dan omega 6 (asam linoleat). Ig.A tidak diserap, tetapi dapat melumpuhkan bakteri patogen E.coli dan berbagai virus pencernaan. Sejenis protein komponen zat kekebalan tubuh Enzim yang melindungi bayi terhadap bakteri E.coli dan Salmonella serta virus. Pada ASI 2 minggu pertama terdapat lebih dari 4000 sel/mL. Terdiri atas 3 macam, yaituBronchus Asociated Lympocyte Tissue (BALT)/antibodi pernapasan;Gut Asociated Lympocyte Tissue (GALT)/antibodi saluran pernapasan; dan Mammary Asociated Lympocyte Tissue(MALT)/antibodi jaringan payudara ibu. Menunjang pertumbuhan bakteri Lactobacillus bifidus yang menjaga flora usus bayi. |
Kelenjar mamae mengalami pematangan pada wanita sewaktu mengalami pubertas. Namun, hanya setelah wanita melahirkan saja kelenjar mamae mengalami perkembangan dan pematangan akhir menjadi kelenjar yang menyekresikan air susu. Sekresi kelenjar mamae ini merupakan respons terhadap hormon progesteron dan estrogen. Pada bulan ke tiga atau ke empat kehamilan, kelenjar mamae mulai menyintesis dan menyimpan cairan kuning yang disebut kolostrum, dalam jumlah yang sedikit. Kolostrum akan menjadi makanan pertama bagi bayi. Kolostrum mengandung banyak antibodi ibu yang akan membantu bayi dari infeksi. Selain itu, mengandung banyak protein yang dapat mencegah diare.
Beberapa hari setelah dilahirkan, bayi akan mulai disusui. Proses menyusui jika dikombinasikan dengan hormon prolaktin dari kelenjar hipofisis akan menstimulasi sintesis ASI. Sewaktu plasenta dipisahkan antara bayi dan ibunya, progesteron dan estrogen dari plasenta tidak dapat lagi menghambat pengeluaran prolaktin. Setelah produksi susu dimulai, hubungan fisiologi dan psikologi antara ibu dan anak terjadi. Bayi secara insting mengisap puting payudara, menyebabkan terjadinya pengiriman impuls kepada otak ibu untuk menghasilkan prolaktin dan oksitosin dari kelenjar hipofisis. Prolaktin merangsang produksi ASI lebih banyak, sedangkan oksitosin merangsang sekresi ASI. Pemberian ASI saja atau yang dikenal dengan ASI eksklusif, selama 6 bulan pertama dianjurkan oleh badan kesehatan dunia (WHO). Hal ini didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya tahan tubuh bayi, pertumbuhan, dan perkembangannya. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama tidak memerlukan penambahan cairan atau makanan lain. Rata-rata kebutuhan cairan bayi sehat sehari berkisar 800–100 mL/kg berat badan dalam minggu pertama usianya. Pada usia 3–6 bulan, sekitar 140–160 mL/kg berat badan. Jumlah ini dapat dipenuhi cukup dari ASI eksklusif dan tidak dibatasi (sesuai ‘permintaan’ bayi, siang dan malam). Selain itu, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dapat menghemat pengeluaran rumah tangga.
Pemeriksaan Sebelum Kehamilan: Faktor Rh
Pemeriksaan kondisi pasangan sebelum menikah sangat baik dilakukan untuk mengurangi risiko yang akan timbul pada bayi. Salah satu pemeriksaan yang umum dilakukan adalah pemeriksaan golongan rhesus (Rh) darah calon ibu dan anak. Walaupun tidak mungkin untuk menggagalkan pernikahan yang akan dilaksanakan, tetapi dengan pemeriksaan ini diharapkan calon orangtua dapat melakukan perencanaan yang matang terhadap keluarga yang akan dibentuknya kelak.
Terdapat 85% manusia memiliki protein tertentu dalam darahnya yang menentukan sifat Rh darahnya (positif atau negatif). Rh positif bersifat dominan terhadap Rh negatif sehingga apabila seorang wanita mempunyai Rh negatif dan suaminya mempunyai Rh positif, anaknya akan mempunyai Rh positif. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penolakan bayi oleh tubuh ibu. Hal ini telah Anda pelajari dalam Bab SistemPeredaran Darah. Pada kehamilan pertama, penolakan tubuh ibu tidak terlalu tampak. Rh positif yang dikandung oleh anak pada kehamilan pertama belum direspons secara maksimal oleh sistem imun tubuh ibu. Namun, telah dipersiapkan jika terjadi serangan Rh positif yang kedua. Oleh karena itu, pada kehamilan kedua, bayi akan diserang oleh sistem imunitas tubuh ibu karena dianggap Rh positif adalah protein asing yang harus dilawan. Antibodi tubuh ibu ini akan membuat darah bayi menggumpal sehingga dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Kasus kematian bayi akibat ketidakcocokan Rh ini disebuteritroblastosis fetalis.
Terdapat 85% manusia memiliki protein tertentu dalam darahnya yang menentukan sifat Rh darahnya (positif atau negatif). Rh positif bersifat dominan terhadap Rh negatif sehingga apabila seorang wanita mempunyai Rh negatif dan suaminya mempunyai Rh positif, anaknya akan mempunyai Rh positif. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penolakan bayi oleh tubuh ibu. Hal ini telah Anda pelajari dalam Bab SistemPeredaran Darah. Pada kehamilan pertama, penolakan tubuh ibu tidak terlalu tampak. Rh positif yang dikandung oleh anak pada kehamilan pertama belum direspons secara maksimal oleh sistem imun tubuh ibu. Namun, telah dipersiapkan jika terjadi serangan Rh positif yang kedua. Oleh karena itu, pada kehamilan kedua, bayi akan diserang oleh sistem imunitas tubuh ibu karena dianggap Rh positif adalah protein asing yang harus dilawan. Antibodi tubuh ibu ini akan membuat darah bayi menggumpal sehingga dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Kasus kematian bayi akibat ketidakcocokan Rh ini disebuteritroblastosis fetalis.
sumber : http://budisma.web.id/materi/sma/biologi-kelas-xi/fertilisasi-dan-kehamilan/
Mengenai Eritroblastosis Fetalis
Dalam istilah sehari-hari, anak disebut sebagai darah daging ibunya. Wajar disebut demikian karena sejak dalam bentuk zigot, anak terus bertumbuh dan berkembang dalam rahim ibunya seolah-olah anak tersebut berasal dari darah dan daging ibunya.
Ternyata secara ilmiah, terbentuknya zigot sampai menjadi janin dalam tubuh ibu sampai akhirnya lahir menjadi seorang anak tidak sesederhana itu. Darah yang terbentuk dalam tubuh anak dapat berbeda dari ibunya, bahkan suatu faktor yang terkandung dalam darah anak tersebut dapat menyebabkan terbangkitnya suatu sistem imun dalam darah ibunya yang kemudian “menggempur†sel darah anaknya sendiri.
Eritroblastosis Fetalis misalnya, merupakan suatu kelainan berupa hemolisis pada janin yang akan tampak pada bayi yang baru lahir karena inkompatibilitasgolongan darah dengan ibunya. Inkompatibilitas ini menyebabkan terbentuknya sistem imun ibu sebagai respon terhadap sel darah bayi yang mengandung suatu antigen.
Kelainan hemolitik ini dapat disebabkan oleh inkompatibilitas faktor Rh. Faktor Rh ini bersifat dominan, artinya seseorang yang memiliki satu saja copy faktor Rh dalam gennya dinyatakan Rh positif, sedangkan yang tidak punya copy faktor Rh dalam gennya digolongkan sebagai Rh negatif. Ibu dengan Rh – dan ayah Rh +, ada kemungkinan anaknya memiliki Rh + karena mendapat faktor Rh dari ayahnya. Hal ini berarti darah ibu tidak punya faktor Rh, sedangkan dalam darah janinnya ada faktor Rh, dan hanya dalam kasus seperti inilah terjadi inkompatibilitas Rh.
Inkompatibilitas golongan darah ABO juga bisa menyebabkan eritroblastosis fetalis. Dalam sistem ini dikenal antigen A dan antigen B. Orang yang mempunyai antigen A dalam sel darah merahnya bergolongan darah A, yang mempunyai antigen B bergolongan darah B, yang mempunyai kedua antigen tersebut bergolongan darah AB, sedangkan yang tidak punya kedua antigen disebut bergolongan darah O. Inkompatibilitas ABO ini terjadi pada ibu dengan golongan darah O dengan janin yang mempunyai antigen A dan atau antigen B.
Pada prinsipnya inkompatibilitas terjadi bila sel darah merah janin yang mengandung suatu antigen yang tidak dimiliki oleh ibu masuk kedalam sirkulasi darah ibu. Antigen tersebut mensensitisasi sistem imun ibu untuk membentukantibodi, yaitu suatu protein yang berfungsi menyerang dan menghancurkan sel-sel yang dianggap benda asing atau membawa benda asing (antigen), dan terjadilah destruksi sel darah merah janin.
Meskipun prinsipnya hampir sama, inkompatibilitas Rh lebih berbahaya daripada inkompatibilitas ABO karena anti-Rh yang terbentuk lebih mudah masuk ke sirkulasi bayi melalui plasenta dibandingkan anti-A atau anti-B.
Meskipun prinsipnya hampir sama, inkompatibilitas Rh lebih berbahaya daripada inkompatibilitas ABO karena anti-Rh yang terbentuk lebih mudah masuk ke sirkulasi bayi melalui plasenta dibandingkan anti-A atau anti-B.
Masalah inkompatibilitas ini belum terlalu bermasalah pada kehamilan pertama karena hanya sedikit darah janin yang masuk ke dalam sirkulasi darah ibu sehingga tidak terbentuk antibodi dari tubuh ibu, baru pada saat melahirkandarah janin banyak masuk ke sirkulasi darah ibu. Terbentuknya antibodisetelahnya tidak berpengaruh pada bayi pertama yang sudah lahir tersebut. Namun, adakalanya perdarahan-perdarahan kecil pada kehamilan menyebabkan darah janin masuk ke sirkulasi ibu dan terbentuk antibodi.
Pada kehamilan berikutnya janin dalam keadaan yang lebih berbahaya karena antibodi ibu yang telah terbentuk setelah proses kelahiran sebelumnya menyerang sel darah janin yang mengandung antigen. Akibatnya sel-sel darah janin mengalami hemolisis hebat.
Hemolisis menyebabkan bayi mengalami anemia. Tubuh bayi mencoba mengkompensasi dengan melepaskan sel darah muda yang disebut eritoblas ke sirkulasi darahnya. Produksi besar-besaran eritoblas ini menyebabkan pembesaran hati dan limpa, dan dapat juga menyebabkan pembentuk jenis sel darah lain seperti trombosit dan faktor pembekuan darah lain berkurang, akhirnya dapat terjadi perdarahan masif.
Hiperbilirubinemia juga terjadi akibat hemolisis, karena, hemoglobin dipecah dan terbentuklah bilirubin. Bayi menjadi jaundice, yaitu terlihat warna kuning pada kulit dan sklera matanya. Bila tak teratasi, bisa terjadi kernikterus yaitu bilirubin tertimbun di otak yang membahayakan janin. Gejala lainnya adalah hidrops fetalis, yaitu akumulasi cairan dalam tubuh janin (edema). Akumulasi cairandalam rongga dada menyebabkan hambatan nafas bayi.
Untuk meminimalisasi bahaya eritroblastosis fetalis ini, hendaknya dilakukan pemantauan sejak dini. Apabila ada potensi inkompatibilitas pada golongan darah ibu dan anak, misalnya ibu dengan Rh-negatif dengan suami yang Rh-positif, sebaiknya dilakukan pemantauan berkala antibodi yang terbentuk dalam darah ibu. Bila memungkinkan dapat dilakukan amniosintesis ataupun pengambilan darah janin dari umbilical cord sehingga golongan darah janin dapat diketahui. USG juga dapat menjadi alternatif pemantauan untuk mendeteksi adanya hidrop fetalis. Apabila ada tanda bahaya dan kehamilan telah berusia 32-34 minggu hendaknya kehamilan segera diakhiri dengan segera melakukan proses kelahiran.
Pada bayi yang sudah lahir dapat dilakukan transfusi darah untuk mengatasianemia dan juga perdarahan. Fototerapi dilakukan untuk membantu mengatasi hiperbilirubinemia. Bayi juga bisa diberi oksigen dan cairan berisi elektrolit dan obat-obatan untuk mengatasi gejala-gejala yang timbul (pengobatansimptomatis).
Untuk kehamilan kedua dari ibu yang janinnya mengalami eritroblastosis fetalis pada kehamilan pertama, hendaknya berkonsultasi dengan dokter sesegera mungkin.
sumber : http://www.tanyadok.com/anak/mengenai-eritroblastosis-fetalis








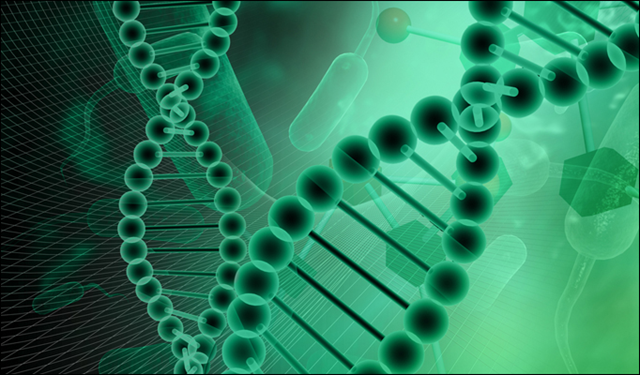
 Senin, Desember 17, 2012
Senin, Desember 17, 2012
 AINUR ROHMAH
AINUR ROHMAH













